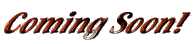Mall dan penghancuran pasar tradisional
(5.13.2008)
Kota sebagai penanda peradaban dimulai dari jalur perdagangan yang disinggahi oleh saudagar dari berbagai negeri, metropolitan Indonesia saat ini berawal dari sana menjelma menjadi sosok raksasa yang menakutkan. Alun-alun kota sebagai penanda kota yang berfungsi sebagai mediasi perkembagan demokrasi, tapi itu dulu.Ketika era mal muncul di era 90-an di kota-kota besar Indonesia, kegairahan massa beralih ke mall dan memalingkan alun-alun sebagai fungsi public yang menyangga demokrasi yang sehat karena berfungsi sebagai public share. Mal tidak sekedar sejumlah petakan-petakan outlet jual beli yang dipersewakan tetapi sekaligus menawarkan sihir yang luar biasa, citra mal sebagai pusat belanja yang tren tidaklah jatuh dari langit.
Sebelum era mal, kita mengenal pusat perbelanjaan yang berskala menengah atau pusat pertokoaan tapi sebagian besar aktivitas ekonomi belum merebak menjadi sihir consumtifisme. Mal menawarkan berbagai kemudahan yang dapat dinikmati oleh konsumen dimana tersedia berbagai kebutuhan dalam satu bangunan mewah mentrend, mulai dari urusan perut, cuci mata hingga urusan perawatan tubuhuh bahkan menyediakan area permainan anak/keluarga, singkatnya segala urusan hidup anda semuanya ada disana. Orang-orang yang datang di mal bukanlah kelas sandal jepit yang terbelit kesusahan hidup, meskipun ada hanya datang menyiksa hasrat atau sebagai karyawan.
Masyarakat pun menganggap mal sebagai simbol kemoderenan dan kamajuan kota yang akan mempermudah hidupnya dan dapat membanggakanya sebagai warga kota. Dalam poling harian Fajar beberapa bulan lalu mengenai pembangunan mal bawa tanah karebosi, dimana sebagian besar komentar masyarakat mendukung dengan alasan dangkal, mereka menganggap mal bawah tanah sebagai ikon kota seperti Blok M Jakarta, kesesatan berpikir masyarakat semakin sempurna. Meski mal telah memberi kemudahan berbelanja dan pendapata pada kas Negara tetapi menghancurkan prekonomian pasar-pasar tradisional dimana prekonomian dikuasai oleh segelintir orang bahkan dapat berimplikasi pada hancurnya ekonomi subsistem yang dikelola mandiri oleh rakyat
Ada beberapa mal dan pusat perbelanjaan besar atau ritel yang menghacurkan pasar-pasar tradisional di negeri ini, berbondong-bondongnya konsumen menyerbu mal menyebabkan berkurangnya pelanggan pasar tradisional yang memiliki sejarah panjang. Kemudahan berbelanja dan ditunjang fasilitas yang nyaman membuat para konsumen ke mal atau pasar ritel, perbandingan antara mal dan pasar tradisional secara pisik memang lebih ‘kren’ mal tapi ada sesuatu yang hilang dalam transaksi mal. Konsumen hanya sekumpulan manusia diam yang hanya bisa bertatap-tatapan tanpa ada komat-kamit, meskipun berbicara hanya sekedar basa-basi atau bertanya letak barang, seni tawar-menawar hilang digantikan tempelen harga, konsumen bukanlah keluarga besar bagi para penjual tapi sekumpulan capital yang penghasil laba, bahkan hak konsumen terkadang diabaikan
Antonio Gramschi mengigatkan, hegemoni berjalan sukses ketika kelas tertindas terobsesi dengan ideology kelas berkuasa, begitulah kiranya pandangan masyarakat yang menganggap mal sebagai penanda kemajuan dan modernitas kota metro, sekali lagi dan sekali lagi mal tak ada urusanya dengan kemajuan taraf peradaban karena disanalah kita temukan manusia modern paling nyata. Modernitas tak ada sangkut pautnya dengan kehausan berbelanja, justru modernitas menempatkan akal untuk berpikir sehat. Mitos kemajuan ini digunakan alat untuk meraup keuntungan besar yang berujung hancurnya pasar-pasar tradisional, di pasar bukan sekedar mencari untung juga lahir kebersamaan dan kebudayaan sebuah masyarakat. Tahukah anda berapa karyawan pasar tradisional yang terpaksa di PHK karena sepinya pengunjung?. Saat ini ada ratusan ribu orang menggantungkan hidup mereka disana, masihkah anada senang berbelanja di mal???
Posted in Label: Gambaran materi