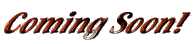Terminologi poskolonial dipahami sebagai sikap dan gerakan resisten terhadap otoritarianisme kolonialisme militer, politik dan rejim-rejim wacana yang terus menerus dibangun oleh penguasa kolonial. Pemaknaan ini memperlihatkan pengaruh kuat teori (linguistik) post-strukturalisme yang kemudian dielaborasi lebih jauh oleh tiga tokoh kritik poskolonial berpengaruh, yaitu Edward Said, Gayatri Spivak, dan Homi Bhabha. Studi (pendekatan) poskolonial yang diaplikasikan di sini bukan dimaksudkan sebagai studi mengenai bekas-bekas wilayah koloni (ex-colonies), konsep poskolonial maupun penggunaannya difokuskan pada “analisa dan pengujian terhadap cara-cara (trik-trik) manipulatif dalam proses budaya yang menentukan karakteristik suatu politik. Studi poskolonial menempatkan agendanya pada wacana representasi pengungkapan tentang bagaimana peradaban Dunia Ketiga diproduksi (dihasilkan) melalui pengalaman kolonial. Pendekatan poskolonial juga men-tidakstabil-kan wacana mengenai relasi “the West and the Rest” (dunia maju-Barat dan dunia lain-yang tertinggal) yang selama ini diasumsikan melalui kategori biner (contohnya: developed-less developed; civilised-uncivilised; dan lain-lain)
Negara Dunia Ketiga sebagai kesatuan poskolonial memiliki luka atau trauma penjajahan yang terus ikut serta dalam setiap proses pembentukan jati diri kebangsaan. Menurut Leela Gandhi, negara-bangsa poskolonial cenderung berusaha lepas dari luka tersebut dengan mengupayakan sebentuk diskontinuitas terhadap masa lalu yang menyakitkan itu. Hal ini menyuburkan tumbuhnya amnesia sejarah yang menjadikan masyarakat tercerabut dan tidak pernah bisa kembali pada identitasnya semula, yakni identitas sebelum mengalami penjajahan. Sedemikian besar pengaruh penjajahan, sehingga mempengaruhi pola pikir, pola penghayatan hidup serta pola perilaku masyarakat poskolonial. Negara-bangsa yang terbentuk pun seolah mengalami krisis identitas atau krisis percaya diri, tidak memiliki pegangan yang jelas sehingga mudah digoyahkan dan diombang-ambingkan oleh relasi ketergantungan.
Ketergantungan sebagai konsekuensi logis dari efek lanjutan kolonialisme ini kita temui di dalam globalisasi. Globalisasi juga melahirkan formasi identitas politik yang karakteristiknya dapat kita kenali melalui praktek dan struktur “dominasi serta resistensi”.
Arturo Escobar menggambarkan bahwasanya identitas Dunia Ketiga dibangun dibawah bayang-bayang hegemoni Dunia Pertama. Khususnya ketika masyarakat di Dunia Ketiga memproyeksikan peradaban mereka melalui pencapaian-pencapaian material. Ia melanjutkan kritik-nya dengan melihat isu “kemiskinan” sebagai proyek utama di dalam agenda pembangunan di Dunia Ketiga yang indikatornya memperoleh kategori pembeda dari pencapaian material Dunia Pertama, dimana intervensi yang dilakukan oleh Dunia Pertama (misalnya oleh Bank Dunia―World Bank) mengabaikan aspek-aspek perkembangan kultural yang berlangsung di Dunia Ketiga. Dalam konteks tersebut, bukan hanya “negara” yang ditransformasikan ke dalam obyek pembangunan oleh kekuatan representasi wacana pembangunan, melainkan juga orang―manusia―nya. Meski demikian, pendekatan poskolonial tidak hanya semata-mata menilai efek negatif yang dilahirkan oleh modernitas global, tetapi juga melihat kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat di Dunia Ketiga untuk menegosiasikan posisi resistensi mereka di dalam struktur modernitas itu sendiri. Upaya pencarian semacam ini, misalnya, dipelopori oleh Vandana Shiva yang menggagas penemuan kembali nilai-nilai lokal yang menandangi efek negatif dari proyek modernitas Barat.
Meskipun upaya yang dirintis oleh Vandana Shiva pada awalnya hanya merupakan gerakan yang bersifat lokal, akan tetapi globalisasi yang memungkinkan suatu gerakan ditransformasikan melalui diseminasi wacana dan difasilitasi oleh teknologi telah membuat gerakan alternatif semacam itu kini mulai melintasi batas-batas nasional (transnasional). Dari sini ungkapan Michael Keith dan Steve Pile (1993), menjadi relevan, ia menyarankan tiga lokasi bagi batasan-batasan dalam “politik identitas baru (postmodern)”, yakni: (1) lokasi bagi perjuangan (location of struggle); (2) komunitas resistensi (communities of resistance); dan (3) ruang-gerak politik (political spaces). Lokasi bagi perjuangan (location of struggle) merupakan suatu ruang dimana individu memasuki politik. Ruang ini dapat bersifat riil (real space), imajiner (imaginary space), atau simbolik (symbolic space). Komunitas resistensi memerlukan suatu landasan (baik yang bersifat riil, imajiner, ataupun simbolik) yang memungkinkan tumbuhnya formasi aliansi politik dan pemberdayaan aliansi dalam kelompok-kelompok marginal. Oleh karena itu komunitas resistensi memperjuangkan ruang gerak bagi politik identitas sebagai upaya penciptaan alternatif-alternatif kemungkinan-kemungkinan politis (the alternatives of political possibilities).
Lewat materi ini peserta diharapkan dapat merumuskan inisiasi gerak dalam ranah kebudayaan baik secara personal maupun kolektif. Semoga
Posted in Label: Gambaran materi